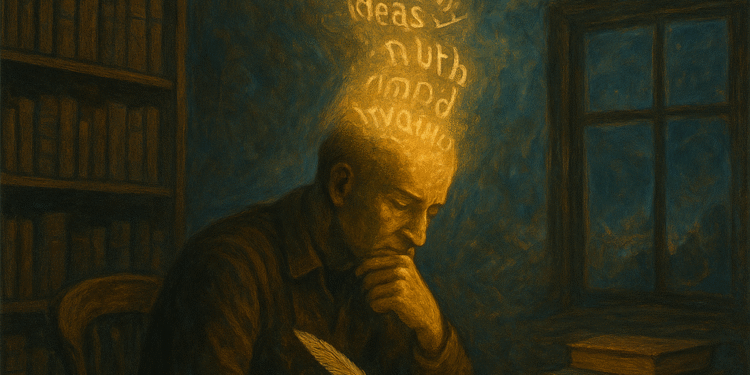Konsep apresiasi terhadap karya sastra dari masa ke masa terus mengalami perkembangan. Salah satu indikator dari fenomena tersebut tak jarang lahir dari dinamika pemikiran yang juga senantiasa bertransformasi di setiap zaman. Aspek dari perkembangan tersebut pun beragam, mulai dari budaya, sosial, bahkan politik.
Jika ditilik dari segi historis sastra itu sendiri, formalisme bisa dibilang menjadi titik tolak awal dari berkembangnya objektivitas penilaian suatu karya. Pertama kali muncul di Rusia sekitar awal abad 20, pemikiran ini mengkritik konsep apresiasi pragmatis yang berpedoman pada konsep kaitan dengan kehidupan sosial dan pandangan hidup. Di mana dari sudut pandang formalisme, karya sastra pada dasarnya dapat diteliti dari segi isi dan bentuknya sendiri.
Antara Formalisme dan Pragmatisme
Seperti yang telah dijelaskan secara singkat di atas, salah satu fenomena yang menjadi bahan kritik dari formalisme adalah pendekatan pragmatik. Di mana konsep pragmatik sendiri. mengutip dari M.H. Abrams, berfokus pada eksplorasi intelektual, dampak emosional, serta etis yang ada pada karya kepada pembaca. Dari proses ini, sastra dievaluasi dengan indikator baik serta buruknya mengacu kepada efek yang dirasakan oleh si pembaca itu sendiri.
Terlepas dari kelebihan dan kekurangan karya sastra itu sendiri, konsep penilaian, pembentukan, serta pemenuhan kebutuhan dan keinginan pembaca menjadi tugas utama seorang penulis. Endraswara menjelaskan bahwa respons atas sebuah karya dalam pendekatan pragmatis sepenuhnya menjadi wewenang si pembaca. Hak tersebut termasuk menilai, merekonstruksi, serta sepenuhnya meninggalkan reaksi negatif dalam berbagai bentuk seperti marah, kesal, ataupun memutuskan untuk tidak membacanya lagi jika karya tersebut dianggap tidak sesuai dengan indikator baik buruk yang telah ditetapkan oleh pembaca sebelumnya.
Perspektif inilah yang akhirnya mendapatkan kritik dari para kaum formalis yang menitikberatkan apresiasi sebuah karya pada bentuk dan isinya dengan pendakatan fungsi estetika. Aliran yang dipelopori oleh Skhlovsky, Roman Jacobson, dan Sjklovski ini menilai bahwa sebuah karya pada dasarnya berawal dari bahan-bahan yang bersifat netral, sebelum akhirnya disulap oleh sang pengarang menjadi teks dengan pembiasan yang menghilangkan otomatisasi pemahaman sang pembaca.
Maka dari itu, diperlukan pendekatan yang lebih objektif dalam menilai sebuah karya sastra daripada hanya sekadar relevansinya dengan pembaca. Hal ini ditegaskan dalam buku Duktur Abdul Athi Al-Kiwan yang berjudul Nazhriyyat Al-Adabiyah wa Manahij An-Naqd, dalam buku tersebut, mengutip dari Jacobson, beliau menjelaskan bahwa pemahaman tentang ilmu sastra pada dasarnya bukan sastra itu sendiri, melainkan memiliki sifat sastrawi. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian terhadap sastra harus dibatasi hanya pada teks karya.
Pendalaman ini, menurut Duktur Abdul Athi Al-Kiwan, merupakan upaya untuk membatasi aspek ideologi sosial di Rusia yang mendominasi objektivitas terhadap penilaian karya pada saat itu. Bahkan menjadikan publik melihat sastra hanya sebagai simbol dan justru melemahkan karya karena harus tunduk pada dominasi sosial tadi. Menjadikan sastra terus mengikut pada ideologi masyarakat yang berkembang saat itu, tanpa ada ruang untuk dipahami secara objektif, juga untuk menuangkan kritik dan inovasi pada pemikiran.
Penerapan Formalisme, Ulasan Bahasa, dan Tuntutan Pendalaman Teori
Roman Jacobson, salah satu tokoh yang memiliki peran sentral dalam perkembangan pandangan formalisme ini berpendapat bahwa teori puitika dan sastra tidak bisa terlepaskan dari bahasa. Dalam penerapannya, Jacobson membawa ide tentang komunikasi dalam teks, di mana terdapat fungsi-fungsi yang harus dipahami demi mencapai pemahaman yang sesuai antara si penulis dan pembaca.
Adapun Jacobson menerapkan tiga fungsi, yakni referensial (mengacu pada konteks teks), emotif (mengacu pada pembaca), dan puitis (mengacu pada estetika). Berkaitan dengan ketiga fungsi di atas, Jacobson menitikberatkan perspektifnya pada fungsi puitis, di mana pemilihan kata dan susunan kalimat menjadi perhatian utama. Hal ini ditujukan untuk menilai kualitas sastra bukan hanya dari konteks, melainkan juga nilai estetikanya.
Pengkajian ini juga ditujukan untuk memperdalam komunikasi antara penulis dan pembaca. Dimana untuk memahami serta mengapresiasi sebuah karya, si pembaca mesti mendalami bahasa yang dipakai, juga telah dimanipulasi dan dibastraksikan maknanya oleh si penulis menjadi karya sastra, baik dari segi langue (bahasa formal), maupun parole (bahasa percakapan sehari-hari).
Lebih jauh, Duktur Athi Al-Kiwan dalam bukunya menjelaskan tujuan pendalaman pemahaman bahasa penulis ini juga agar pembaca dapat mengenal lebih dalam tujuan yang ingin disampaikan penulis dari karyanya. Menurutnya, setiap orang yang bersastra tidak pernah lepas dari dua hal, yaitu konteks dan bentuk, di mana untuk bentuk sendiri, setiap orang bisa muncul dalam wujud pembawaan yang berbeda-beda, khususnya dari segi parole. Di mana ada potensi besar perbedaan pemahaman konteks dari manipulasi bahasa yang dilakukan penulis untuk melahirkan karya. Lebih lanjut, Jacobson juga menjelaskan adanya kode-kode cakapan yang bisa jadi juga dimuat oleh para penulis dalam karyanya, menjadikan produk sastra tersebut memerlukan kajian lebih mendalam untuk diapresiasi.
Tuntutan ini pun berlaku untuk langue, David Bunchbinder dalam salah satu pernyataannya mengenai kritik sastra menekankan pentingnya kemampuan bahasa si pembaca dalam melaksanakan pencarian makna karya. Hal ini mencakup pendalaman terhadap semua teori dan kaidah bahasa formal yang dipakai atau memang merupakan bahasa asli penulis. Misalnya, untuk mengkaji puisi-puisi Arab, kita perlu kedalaman ilmu-ilmu bahasa seperti nahwu, balagah, arudh, dan sebagainya. Begitu pun untuk sastra Indonesia, pemahaman terkait majas serta pengulangan dan keselarasan bunyi diperlukan untuk sampai pada tingkat apresiasi yang lebih dalam.
Pendalaman terkait bahasa ini, terutama dari fungsi estetika yang mencakup di antaranya rima, ritme, dan bunyi pada akhirnya dianggap oleh Bucbinder sebagai media untuk mengapresiasi atau mengkritik suatu karya. Dengan penerapan kaidah bahasa serta pengkajian fungsi puitis, seseorang dapat menilai, meneliti, mengkritik, memahami permasalahan utama yang dibawa oleh karya, menentukan poin-poin kelemahan dan kekuatan karya tersebut, dan sebagainya.
Praktik Sosial Formalisme, Memahami Bahasa sebagai Pintu Ideologi Sosial
Tokoh yang mencanangkan penggabungan antara dua pemikiran ini (formalisme dan marxisme) adalah Mikhail Bakhtain. Menginisiasi konsep dialogis dalam observasi bahasa dan budaya, Bakhtin membawa argumen materialisme yang menyatakan bahwa sastra adalah aspek ideologis yang dipengaruhi oleh realitas sosial, dimana perkembangannya dianggap sebagai perkembangan struktur ekonomi antar kelas.
Sementara dari segi formalismenya, Bakhtin menjelaskan bahwa setiap ideologi pada dasarnya memiliki bahasanya sendiri, yang segala aturan di dalamnya mempunyai perbedaan dan karakter masing-masing. Mulai dari sini, konsep dialogis Bakhtin bisa diterapkan. Menurutnya, dalam konsep dialogis terdapat keterkaitan yang erat antara setiap individu. Manusia secara siklus seringkali mendapatkan pemahaman terkait suatu hal justru dari orang lain, baik itu bersifat eksternal maupun internal dirinya sendiri.
Fenomena inilah yang menjadikan konsep dialog terjadi secara otomatis dalam kehidupan, di mana manusia mendapatkan jawaban atas dirinya melalui alam sadar orang lain. Dari segi sastra, alam sadar tersebut dibahasakan dalam bentuk susunan kalimat yang telah dimanipulasi oleh penulis dengan kreativitasnya sebagai karya sastra. Di mana pembacaan terkait hal tersebut secara tak langsung menjadi dialog (perpindahan ideologi) antara si penulis dan si pembaca. Hal ini dijelaskan oleh Bakhtin dari hasil kajiannya terhadap novel karya Tolstoy dan Dostoevsky.
Untuk menerapkan dialog ini, Bakhtin membawa dua konsep yakni heteroglossia dan carnivalesque. Heterologssia yang dibahas Bakhtin dalam In the Dialogical Imagination berfokus pada pembahasan tentang kombinasi pernyataan atau genre bicara, misalnya polifoni, jargon, dan dialek yang dipakai untuk mengungkapkan wacana. Heterologssia menekankan keterkaitan dialog antara satu individu dengan lainnya dalam bahasa yang berbeda. Konsep ini tidak hanya bisa dipakai untuk mengaplikasikan kritik, tapi juga dari segi pembangunan karya itu sendiri.
Perspektif ini didasari oleh pemahaman bahwa setiap suara atau kata muncul dari hasil dialog yang bermaksud menjawab permasalahan dalam kehidupan. Dengan konsep ini, kata-kata dikonversi menjadi suatu objek. Di mana dalam kajian novel Bakhtin, ia berpandangan bahwa setiap novel yang dibuat melalui proses dialogis akan memunculkan berbagai dimensi suara yang menciptakan konsep artistik yang terstuktur. Ini pun dipengaruhi oleh intensi penulis dalam mengekspresikan bahasa yang ia tuangkan dalam karya.
Kita bisa mengambil contoh dari perbedaan puisi antara Joko Pinurbo yang mengacu pada romantisme dan Saut Situmorang yang realis dan selalu penuh dengan kritik. Penerapan bunyi dalam puisi-puisi Jokpin seperti di Telepon Genggam, dan Kamus Kecil selalu berdasar pada efoni yang berfokus pada keselarasan bunyi dan harmonisasi, semua itu cocok dengan tujuan si penulis yang seringkali dalam puisinya kita dapati ingin meromantisasi kehidupan.
Sementara Saut dalam antologi Negeri Terluka menuangkan tulisannya dengan nuansa kakofoni, dimana banyak suara sumbang, bising, dan mengganggu yang lahir dari ketidakselarasan bunyi. Hal ini ditujukan untuk melahirkan kesan disturbing dalam puisinya yang memang seringkali membahas tentang dekadensi kehidupan dan moral, baik dari segi sosial, politik, maupun ekonomi.
Begitu pun dalam puisi-puisi Arab, dimana penggunaan bahr dalam syair-syair klasik dapat menjadi tolok ukur relevansi estetika sastra tersebut, misalnya bahr madîd yang cocok untuk puisi rayuan, atau bahr mutadârik untuk mencela, dan bahr tawîl yang sering dipakai untuk berbangga-bangga.
Dialog yang terjadi antara penulis dan pembaca dijembatani oleh bahasa. Pada titik ini, melalui konteks heterologgsia tadi, pembaca harus bisa mendalami intensi penulis melalui media bahasa dan bunyi. Membaca bukan hanya konteks kalimat, tapi juga kesan intuitif yang ingin ditinggalkan penulis dalam untaian katanya. Kemudian, jika memiliki kapasitas dalam bidang bahasa, pembaca juga dapat meneliti titik relevansi tujuan kesan tadi dengan tipikal pembahasaan yang dipakai penulis.
Dengan membawa konteks sosial di dalamnya, heterologssia Bakhtin menjadi selangkah lebih dekat dalam mengenal karya dan penulis daripada Jacobson yang menitikberatkan kajiannya hanya pada teks. Sebab menawarkan ruang lebih terbuka untuk pembaca mengenal penulis dengan memandang bahasa yang dipakai sebagai media ideologi, bukan hanya pembacaan makna teks.
Sebab meskipun kajian sastra menjadikan bahasa teks sebagai objek penelitian utama. Menurut Bakhtin, dunia bahasa itu sendiri tidak dapat berhubungan langsung dengan dunia luar yang seringkali menjadi pembahasan dalam sastra, namun interaksi sosial mampu mengakses dan menjadikan bahasa sebagai alat untuk memediasi dialog antar orang dan pemikirannya masing-masing. Fenomena ini pun relevan dengan penerapan sastra sebagai wadah perpindahan ideologi tadi.
Konsep heterologssia ini juga bisa diaplikasikan dalam penulisan sebuah karya, dengan dibekali kedalaman teori kebahasaan seperti yang telah ditegaskan Buchbinder di atas. Kita bisa mengobservasi bahasa dan suara di sekitar kita dan memutuskan penerapan yang cocok dengan produk yang ingin kita tulis. Meskipun tanpa landasan teori, fenomena ini seringkali terjadi secara tidak sadar setiap kita ingin menulis sesuatu. Di mana pada dasarnya, Bakhtin pun mengakui bahwa heterologssia ini juga bekerja dalam ranah sosial, beragam suara dan gaya didapatkan dari orang lain, hal ini merupakan penerapan kreativitas penulis dengan konsep imitasi Plato yang alam idenya muncul dari hasil observasi heterologssia sosial.
Adapun konsep selanjutnya adalah carnavalisque, Bakhtin mendefinisikannya dalam konteks karnaval yang berkaitan dengan canda tawa, pembawaan bahasa canda tawa ini biasanya dikemas dalam bentuk parodi. Namun tidak hanya sekadar parodi, dalam penerapan sastra, konsep karnaval ini hadir sebagai media perpindahan ideologi dalam bentuk yang hegemonis.
Sama dengan heterologssia, pemahaman ini lahir dari perpaduan antara formalism dan marxisme. Carnavalisque berfokus pada kesetaraan sosial, dalam hal ini berarti memperlakukan dunia sebagai milik bersama tanpa tatanan sosial, di mana setiap perspektif secara terbuka dituturkan dan diapresiasi tanpa mempertimbangkan konteks elitis.
Dalam carnavalisque, penerapan satir dan ironi dengan konsep parodi menjadi titik utama secara tak langsung juga menambahkan kesan unik dan menyenangkan dalam sastra. Melalui konsep ini, pembaca tak hanya harus memahami maksud kalimat, melainkan juga konteks fenomena yang dibawakan oleh struktur artistik bahasa penulis. Bakhtin melalui konsep ini, mencoba memaparkan ambivalensi komedi yang bisa diterapkan sebagai alat propaganda ideologi dalam karya.
Penutup
Meskipun secara konteks bertolak belakang, sastra dan sosial pada dasarnya merupakan suatu yang tidak terpisahkan. Formalisme sendiri hadir sebagai pelopor untuk menerapkan sosial pada sastra dengan cara yang objektif dan adil. Membawa batasan pragmatis yang dianggap terlalu menuhankan sosial, lalu mencanangkan kaidah agar sosial itu sendiri dapat menjadi penyokong untuk setiap karya, baik dari segi apresiasi maupun kritik terhadapnya.
Teori-teori ini, dalam penerapannya terus berkembang hingga saat ini. Formalisme sendiri menjadi pembuka untuk teori kritik strukturalisme yang dapat diaplikasikan pada karya dari berbagai zaman. Menerapkan penelitian pada setiap karya demi melahirkan dialog yang ideal dari setiap era, baik dari masa lalu maupun untuk masa depan.