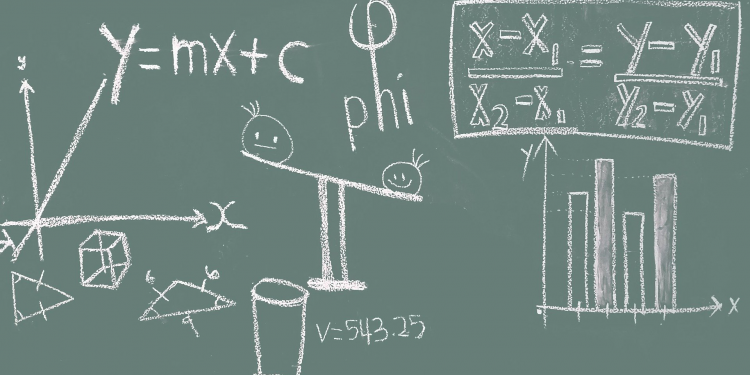Pada pembahasan luzum sebelumnya, kita mungkin mengira luzum itu hanya sekedar keterkaitan api dan panas, es dan dingin, dan lain-lain. Sebenarnya, contoh demikian dirancang untuk memudahkan kita memahami keterkaitan dua hal. Lebih tepatnya, keterkaitan logis.
Dalam diskusi dan percakapan sehari-hari, kita akan bisa merasakan manfaat luzum ini dan sebenarnya tujuan luzum dirancang, agar kita bisa memanfaatkannya di kehidupan kita dalam bentuk percakapan, bukan lagi sekedar api dan panas atau apalah.
Saya ingin memberikan satu contoh kasus. Anggaplah ada orang di hadapan anda membahas tentang prestasi temannya. Dalam penjelasannya, dia juga menceritakan hal-hal yang bisa dibanggakan dari temannya, sampai berkaitan dengan belajar, kehidupannya, dan hal-hal yang bisa diteladani darinya. Tapi, kalau kita mau main asumsi atau perasaan, apakah mungkin ada yang berpikiran “wah, orang ini mau merendahkan dan menganggap remeh kita” atau “dia pasti fanatik terhadap temannya“? Jawabannya, mungkin. Tapi, kalau kita menggunakan teori luzum ini, prasangka seperti itu bisa kita tepis perlahan. Mari kita uji prasangka itu.
Mari perhatikan lagi kasus itu, lihat apa yang diceritakan. Ya, dia menceritakan hal-hal positif dari temannya. Tapi, ada prasangka negatif yang muncul dari tindakan orang itu, yakni menganggap orang ini “meremehkan” dan “fanatik”. Kalau kita mau berpikir, apa keterkaitan logis antara menceritakan hal positif dari seorang teman dengan meremehkan orang lain? Tidak ada. Buktinya, kita bisa menceritakan hal positif dari orang lain tanpa ada setitik pun niat meremehkan orang lain. Sementara syarat terjadi keterkaitan logis adalah dua hal yang dianggap berkaitan itu wajib terjadi. Dengan kata lain, ketika kita menceritakan hal positif dari orang lain itu harus terjadi juga adanya niat meremehkan baru bisa dikatakan ada keterkaitan logis atau luzum. Tapi, faktanya tidak. Ada kemungkinan lain di sana. Maka, prsangka buruk pertama itu batal.
Selanjutnya, kita coba uji prasangka buruk kedua, yakni orang tersebut itu fanatik terhadap temannya. Kita bisa bertanya begini, apakah ketika kita menceritakan hal positif dari orang lain itu meniscayakan kefanatikan kita terhadap orang yang kita ceritakan? Dengan pertanyaan lain, apakah gara-gara kita menceritakan hal positif dari orang lain, otomatis kita menjadi fanatik terhadap orang yang kita ceritakan? Jawabannya tidak. Kita bisa buktikan. Misalnya, ada orang yang snagat anda benci, sampai-sampai semua kebaikannya terlibat buruk. Tapi kalau kita mau membuka mata lebar-lebar, seburuk-buruknya orang, pasti ada kebaikan pada dirinya, sekecil apapun itu. Nah, terus anda ceritakan titik positif orang yang anda sangat benci tadi. Apakah gara-gara cerita positif anda tentang orang tadi itu lantas anda menjadi fanatik pada orang yang tadinya sangat anda benci? Tentu tidak. Maka, bisa disimpulkan kalau menceritakan hal positif dari orang lain itu tidak meniscayakan dia menjadi fanatik terhadap orang yang dia ceritakan.
Dari cerita orang tersebut, kita tidak bisa memunculkan konsekuensi dari perbuatannya kecuali itu bersifat pasti. Artinya, kita tidak bisa mengaitkan sesuatu dengan keterkaitan yang sifatnya logis (lâzim) jika konsekuensi itu tidak pasti terjadi, seperti kasus orang di atas tadi. Hanya menceritakan hal positif dari orang lain, langsung dikatakan meremehkan atau fanatik. Berbeda kasusnya jika orang tersebut menceritakan kisah inspiratif itu dari temannya lalu orang tersebut mengatakan “daripada kalian yang tidak ada apa-apanya, haha (anggaplah ketawa jahat)”, ini sudah bisa kita simpulkan bahwa dia menceritakan untuk meremehkan orang lain yang menjadi pendengar. Mengapa? Karena dua hal tadi itu sudah lazim, alias wajib terjadi pada kasus ini. Yakni, dia memang menceritakan untuk meremehkan orang itu sudah jelas. Karena kemungkinan-kemungkinan lain sudah dipatahkan dengan ungkapannya yang terus terang memiliki kelaziman meremehkan orang. Buktinya, kalau orang mengatakan itu, apalagi sambil ketawa jahat, jelas meremehkan kita dan kita juga merasa diremehkan.
Timbul pertanyaan, bagaimana jika orang tersebut mengeluarkan kalimat ungkapan tapi niatnya ingin memotivasi agar orang terpacu dalam belajar dan berbuat baik? Jawabannya, ini tidak membatalkan kejadian meremehkan itu. Karena dia memotivasi dengan cara meremehkan. Selain itu, tidak bisa dikatakan kontradiksi, tidak membatalkan satu sama lain. Sebab, memotivasi satu hal, tindakan meremehkan juga hal lain yang mungkin sama-sama terjadi. Kalau anda perhatikan sekali lagi, mungkin anda akan berkesimpulan kalau di sana terjadi dua perbuatan, yakni memotivasi dan meremehkan.
Itu satu contoh yang bisa saja ada dalam kehidupan kita dan praktik teori luzûm itu tidak luput dari kejadian ini. Selain digunakan dalam percakapan sehari-hari, ini juga bisa terjadi dalam percakapan serius. Misalnya, anda membahas Syi’ah kepada orang banyak. Apa yang terjadi jika anda melakukan itu? Bisa saja anda dituduh Syi’ah hanya karena membahas Syi’ah. Artinya, orang-orang yang mendengarkan pemaparan anda itu menganggap anda Syi’ah, semata-mata karena pembahasan Syi’ah itu. Tapi, kalau mau dipikir, apakah orang yang membahas Syi’ah itu otomatis menjadi Syi’ah? Kita bisa mengujinya. Anggaplah anda kuliah di jurusan perbandingan agama. Tentu yang dibahas di sana adalah beragam agama, ada Islam, Kristen, Budha, dan lain-lain. Nah, ketika anda mendapat tugas untuk membahas agama Kristen, apakah anda otomatis menjadi Kristen gara-gara membahas agama Kristen itu? Jawabannya tidak. Sebab, tidak ada keterkaitan logis antara membahas dan masuknya atau sepakatnya anda dengan suatu ideologi yang anda bahas. Anda bisa saja membahas agama Kristen tanpa harus berkristen. Sebagaimana anda membahas Syi’ah tanpa harus bersyi’ah.
Anak-anak jurusan akidah-filsafat juga tidak jarang menjadi sasaran empuk pertanyaan “anda mau jadi atheis?”. Karena sebagian orang menganggap kalau kita masuk jurusan akidah-filsafat otomatis menjadi atheis. Apakah keterkaitan ini bisa diterima? Tentu kita harus mengujinya juga. Kita bisa mencari tahu, siapa itu Syekh Ahmad Thayyib di gawai kita masing-masing. Singkatnya, beliau adalah Grand Syekh di Al-Azhar atau orang yang memiliki tanggung jawab tertinggi di Al-Azhar saat tulisan ini dibuat. Di antara rekam jejak pendidikan beliau adalah alumni Universitas Al-Azhar pada jurusan akidah-filsafat.
Melihat kejadian di atas, orang mengidentikkan dan mengaitkan jurusan akidah-filsafat itu dengan atheis. Jika kita menerima pikiran demikian, maka kita akan mengklaim Grand Syekh yang memegang tanggung jawab tertinggi di universitas Islam terbesar di dunia itu sebagai orang atheis, sebab beliau adalah keluaran dari jurusan akidah-filsafat. Bisakah kita menerima itu? Jawabannya tidak. Mana mungkin Al-Azhar yang merupakan salah satu aset umat Islam saat ini dan mencetak banyak pemikir plus ulama itu mengangkat seorang atheis menjadi pemegang tanggung jawab tertingginya? Itu tidak masuk akal. Dengan kata lain, orang yang mengambil jurusan akidah-filsafat itu tidak otonatis menjadi atheis. Sebab, mengambil jurusan akidah-filsafat atau lebih tepatnya, belajar filsafat tidak meniscayakan orang tersebut menjadi atheis. Maka, mengambil jurusan akidah-filsafat dan menjadi atheis itu dua hal berbeda dan tidak memiliki keterkaitan logis. Kalaupun ada yang menjadi atheis gara-gara belajar filsafat, itu tidak membatalkan klaim di atas bahwa belajar filsafat itu satu hal, sedangkan menjadi atheis itu hal lain. Sebab, belajar filsafat itu memiliki dua kemungkinan, menjadi mukmin atau tidak. Itu saja. Artinya, keatheisan orang gara-gara belajar filsafat tidak otomatis menghilangkan kemungkinan orang tetap beriman saat dia belajar filsafat sampai selesai.
Di sini perlu dicatat bahwa dua hal yang berkaitan itu harus wajib. Ini juga berlaku dalam sebab akibat. Penulis ingin memperkenalkan dua istilah yang digunakan dalam ilmu logika, yakni muqaddam (anteseden) dan tâli (konsekuen). Kita tarik satu contoh, misalnya: “Jika saya jatuh dari lantai dua, maka saya merasakan sakit”. Di sini ada dua hal, yakni “saya jatuh dari lantai dua” dan “saya merasakan sakit”. Yang pertama adalah sebab, sedangkan yang kedua adalah akibat. Sebab dalam kalimat ini disebut muqaddam dan akibat dalam kalimat ini disebut tâli. Sebab dan akibat itu harus memiliki keterkaitan logis.
Kita bisa menguji ungkapan itu, apakah memiliki keterkaitan logis atau tidak? Saya tidak tahu apakah semua manusia di dunia ini pernah merasakan jatuh karena terkilir atau tidak. Yang jelas, sebagian besar dari kita ini pernah merasakan jatuh. Ketika kita jatuh di jalanan itu bisa sampai luka dan berdarah, itu sakit. Nah, karena jatuh di jalanan yang jaraknya tidak sejauh lantai dua saja bisa sesakit itu, apalagi kalau jatub dari lantai dua. Dengan kata lain, jatuh dari lantai dua dan merasakan sakit itu adalah dua hal yang memiliki keterkaitan logis. Maka, sebab akibat di sini sah. Karena sebab dan akibat, atau muqaddam dan tâli ini memiliki keterkaitan logis. Akibat itu bisa diterima penyandarannya kepada sebab jika kelaziman atau keterkaitan logisnya itu ada. Jadi, sah jika saya mengatakan “jika saya jatuh dari lantai dua, maka saya merasakan sakit”.
Ada contoh kasus yang sebab akibatnya tidak bisa kita terima karena tidak memiliki keterkaitan logis. Misalnya, saya mengatakan “jika dia makan, maka saya yang kenyang“. Apakah ungkapan hipotesis ini bisa kita terima? Mari kita uji. Ketika orang lain minum, tentu dia yang merasakan hilangnya dahaga itu, bukan orang lain. Tentu, saya juga tidak merasakan hilangnya dahaga itu, karena bukan saya yang minum. Demikian juga makan, dia yang makan, maka tentu yang kenyang adalah dia, bukan saya. Maka di sini kita bisa melihat sebab dan akibat, atau muqaddam dan tâli ini tidak memiliki keterkaitan logis. Maka tidak sah jika dikatakan “jika dia makan, maka saya yang kenyang”.
Dalam pembahasan kesalahan berpikir (logical fallacy), ada namanya strawman fallacy dan confirmation bias. Yang pertama itu kesalahpahaman dari seseorang dalam hal kelaziman dua hal. Dengan kata lain, dia melazimkan dua hal yang tidak ada kaitannya seperti kasus orang yang menceritakan hal positif tentang temannya tadi dan meremehkan orang lain. Sedangkan yang kedua ini kesalahan dalam meletakkan sebab dan akibat. Seperti contoh “jika dia makan, maka saya yang kenyang” tadi. Selain itu, sedikit lebih luas pada poin kedua ini, memang hal tersebut bisa saja terjadi secara aktual dan kejadian aktual itu dijadikan sebagai penguat argumen dalam berinteraksi. Padahal, kejadian itu sama sekali tidak menguatkan ungkapan tersebut. Karena tidak dapat dibuktikan secara rasional. Adapun tentang kesalahan-kesalahan berpikir itu lebih lanjut kita bahas pada kesempatan lain.
Wallahu a’lam