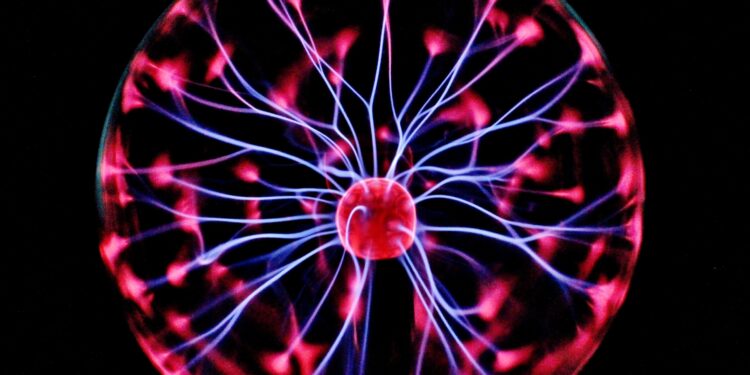Dalam banyak tulisan dan kesempatan, saya selalu menyampaikan bahwa ada sebuah pengantar ilmu kalam yang kurang lumrah terdengar; al-‘umȗr al-‘ammah. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bisa disebut: Persoalan umum. Secara garis besar, persoalan ini memiliki dua garis besar: 1) Filsafat epistemologi. 2) Filsafat ontologi.
Al-‘umȗr al-‘ammah merupakan salah satu pengantar ilmu kalam yang banyak berperan di persoalan ilahiyyât (ketuhanan). Tapi, perlu dicatat, sebagai salah satu pengantar ilmu kalam, bukan berarti ini menjadi satu-satunya ilmu yang mengawal ilmu kalam. Ada ilmu mantik, kategori, debat, dan ilmu wadh’i yang tidak bisa dinafikan perannya.
Jika ini merupakan salah satu pengantar, apakah ini berarti al-‘umȗr al-‘ammah adalah medan yang harus pertama kali untuk kita masuki? Jawabannya, tidak. Selain butuh bekal penalaran kuat dari ilmu mantik, kita juga harus punya bekal pembeda antara Tuhan dan makhluk di ilmu kategori, walau tingkatan dasar. Karena kalau kita tidak punya asas penalaran, maka kita tidak bisa mencerna deretan materi penting di ilmu ini. Juga, kalau kita tidak punya pembeda mana makhluk dan mana Tuhan, maka kita akan memberlakukan hal yang tidak pas kepada Tuhan.
Syekh Ahmad Syadzili, Ahli Ilmu Rasional, dalam pengantar bukunya Al-Madkhal ila Al-‘Umȗr Al-‘Ammah menyatakan bahwa secara khusus, ilmu ini sangat banyak memberikan effort dalam memahami bab ilahiyyât. Bahkan, kalau kita tidak memahami ilmu ini, kita tidak memahami substansi perdebatan antara ulama Sunni, Syi’ah, Muktazilah, Filusuf, dan lain-lain. Dalam buku-buku mereka, istilah kalam yang ada dalam al-‘umȗr al-‘ammah sangat serat dipahami. Dengan kata lain, untuk menelaah buku mereka, menjadi hal yang tidak pernah kita capai.
Di Universitas Al-Azhar, ilmu ini dipelajari secara khusus di tingkatan magister atau strata dua. Kendati demikian, ada juga yang membuka majelis dalam membahas ilmu ini sampai tuntas. Itu seperti yang dilakukan Syekh Husam Ramadhan. Beliau menggunakan buku Misbâh Al-Arwâh fi Ushȗl Al-Dîn, karya Al-Qadhi Nashiruddin Al-Baidhawi. Tapi, sekali lagi, ilmu ini akan serat dipahami jika kita tidak memiliki bekal ilmu rasional lainnya.
Imam Al-Iji, Pendekar Ahlussunnah, setelah membahas seputar pengantar ilmu kalam di Al-Mawâqif, beliau membuka mawqif (bab) baru yang secara khusus berkonsentrasi di persoalan al-‘umȗr al-‘ammah. Setelah itu, mawqif ketiga berisi pembahasan seputar aksiden, lalu mawqif keempat berisi tentang substansi. Setelah pengantar ini, barulah masuk ke pembahasan ilahiyyât.
Begitu juga Khawajah Nashiruddin Al-Thusi, Pendekar Syi’ah, ketika ingin membahas masalah ketuhanan dalam Tajrîd Al-I’tiqâd, semuanya dimulai dari membahas al-‘umȗr al-‘ammah. Setelah itu, membahas seputar substansi dan aksiden. Barulah setelah keduanya, mulai membahas seputar ketuhanan.
Filsafat Epistemologi dan Ontologi
Sekarang, kita memasuki segmen yang lebih serius. Kenapa ilmu kalam tapi dimulai dari epistemologi dan ontologi? Bukannya kalam tidak membahas persoalan rasional? Saya sudah menyinggung sedikit tentang ini dalam salah satu tulisan. Di sana, saya menyatakan bahwa postulat ilmu kalam adalah akal. Sebab, salah satu hal yang niscaya dalam diri manusia adalah akal.
Perlu kita akui bahwa al-‘umȗr al-‘ammah bukanlah pembahasan inti ilmu kalam. Tapi, persoalan ketuhanan, kenabian, dan masalah gaib. Namun, sebagaimana uraian di atas, kita tidak bisa benar-benar memahami substansi bab ketuhanan jika kita tidak memiliki ini. Sebagaimana ilmu mantik, pembahasan seputar signifikasi, lafaz, dan konsep universal bukan substansi ilmu mantik, tapi al-kulliyât al-khamsah (panca-universalis), definisi, proposisi, dan silogisme.
Kenapa epistemologi? Singkatnya, kita mulai dari sebuah kebenaran yang paling dekat. Dari titik ini, kita akan di antar menuju sebuah kebenaran lain yang tingkatannya tidak beda. Ini sudah diisyaratkan di ilmu mantik bahwa dari al-ma’ȗm (hal diketahui), kita bisa mengetahui al-majhȗl (hal tidak diketahui). Baik al-ma’lȗm, maupun al-majhȗl, keduanya merupakan kebenaran, tidak lebih benar salah satunya. Masalahnya hanya pada persepsi kejelasan dari sudut pandang manusia. Jelas atau tidaknya suatu kebenaran di mata manusia, tidak ada pengaruhnya dengan reduksi kebenaran itu sendiri. Kebenaran tetaplah ada tanpa harus diketahui manusia.
Dari mengakui sebuah kebenaran, kita akan mengakui “ada”. Inilah ruang dari ontologi. Dalamnya, akan dibahas apa itu ada, apa itu tiada, dan lain-lain. Juga, kita akan mengakui keberadaan eksistensi eternal dan kontigen. Di sinilah asal-muasal kenapa kita percaya ada sesuatu yang disebabkan dan tidak disebabkan. Dari titik ini juga, api perdebatan antar mazhab bisa kita lihat asalnya.
Tapi, mana duluan apakah pengetahuan (kebenaran) atau ada (eksistensi)? Di sini ada perdebatan serius. Ada yang menyatakan pengetahuan. Jika pengetahuan duluan ada, bukankah saat itu pengetahuan itu “ada”? Atau dengan kata lain, bukankah kita harus mengakui keberadaan terlebih dahulu sebelum mengakui keberadaan pengetahuan? Bagaimana mungkin kita mengakui keberadaan pengetahuan sebelum kita mengakui keberadaan? Namun, jika dibalik, bukankah kita tidak bisa mengakui keberadaan jika kita tidak mengakuinya? Kita tidak akan menyentuh perdebatan ini. Akhirnya, kedua pembahasan ini saling membutuhkan, tidak bisa dipisahkan.
Kalau kita tarik dalam pembahsan ketuhanan, bisakah kita mengakui Tuhan itu ada? Bisakah kita mengakui bahwa kita mengetahui sesuatu yang tidak terindera? Bagaimana mungkin kita bisa percaya ada eksistensi eternal yang tidak disebabkan? Semuanya akan terjawab jika kita mendalami secara serius al-‘umȗr al-‘ammah ini.
Al-‘Umȗr Al-‘Ammah
Sebagian pakar menyebutnya dengan al-umȗr al-syâmilah atau al-umȗr al-kulliyyah karena keluasan cakupannya. Namun, perbedaan penyebutan ini bukanlah hal substansial untuk dibahas.
Para teolog muslim memiliki penafsiran yang berbeda-beda seputar konsep al-‘umȗr al-‘ammah. Setidaknya, ada tiga penafsiran. Kita akan membedahnya satu per satu.
Pertama, penafsiran ini dari datang dari Imam Al-Iji:
ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود من الواجب والممكن
“Pembahasan yang tidak hanya terfokus pada pembahasan wâjib dan mumkin”
Beliau melanjutkan bahwa pembahsan ini ada dua bagian; melibatkan tiga hal dan melibatkan dua hal. Tiga hal tersebut seperti eksistensi yang memiliki sudut pandang. Setiap eksistensi, jika dia banyak, maka dia memiliki banyak kesatuan dengan sudut pandang tertentu. Entah, dia dilihat sebagai mâhiyyah (esensi), maupun tasyakhush (identitas). Kemudian, kedua sudut pandang tadi melahirkan sudut pandang al-imkân (kontigen). Di sinilah lahir sudut pandang jauhar (esensi) dan ‘aradh (aksiden). Singkatnya, tiga hal yang dimaksud adalah wujȗd, wahdah, dan tasyakhush.
Sebagai contoh untuk memahami penjabaran ini, anggaplah saya membeli es krim. Sebagai sesuatu yang ada, saya melihat es krim ini sebagai sesuatu yang ada. Tapi, di saat yang sama, kita juga melihat es krim itu sebagai sesuatu yang memiliki identitas tertentu. Misalnya, es krim ini berasal dari perusahaan yang bernama MCD. Maka es krim ini memiliki identitas yang bernama “Es krim keluaran MCD”. Begitu juga ketika melihat es krim ini sbeagai sesuatu yang memiliki substansi dan aksiden, seperti es krim ini sebagai substansi, memiliki ukuran, warna, rasa, dan lain-lain. Jadi, kita melihat es krim ini dari segi eksistensi, identitas, dan kategorinya.
Sementara yang melibatkan dua hal, itu seperti al-imkân al-khâsh (kontigen khusus), hudȗts (kebaruan), wujȗb bi al-ghair (niscaya dengan sesuatu yang lain), ma’lȗliyyah (kausalitas), dan lain-lain. Untuk lebih memahaminya, kausalitas itu memiliki dua hal; sebab dan akibat. Sebab adalah satu hal. Akibat adalah hal lain. Tapi, keduanya terhimpun dalam hukum yang bernama kausalitas.
Berdasarkan tafisran ini, maka konsekuensinya akan menjadikan pembahasan qidam (eternalitas), ‘adam (nihil), al-imkân al-dzâtiy (kontigen esensial), dan al-wujȗb al-dzâtiy (niscaya esenisial), bukan pembahasan inti kalam, melainkan pembahasan yang “mengikut” saja ke inti kalam.
Kedua, penafsiran ini datang dari Imam Sayyid Syarif Al-Jurjani:
ما يتناول المفهومات بأسرها: إما على سبيل الإطلاق أو على سبيل التقابل
“Sesuatu yang (di dalamnya) terdapat pembahasan tentang konsepsi; baik secara mutlak, maupun oposisi”
Konsep mutlak itu seperti al-imkân al-‘âm. Sebenarnya, konsep ini dibahas belakangan. Tapi, untuk saat ini saya akan memperkenalkan sedikit saja dari konsep ini. Umumnya, di ilmu kalam kita diperkenalkan bahwa jika sesuatu itu sifatnya mungkin, maka dia tidak niscaya. Hal ini tidak perlu pembuktian, senada dengan hukum dasar berpikir. Tapi, ketika sesuatu itu menafikan keniscayaan, maka dia akan memunculkan dua kemungkinan, entah kemungkinan ada atau tidak, misalnya. Jika menafikan dua kemungkinan seperti ini, disebut dengan al-imkân al-khâsh.
Adapun jika hanya menafikan salah satu kemungkinan saja dengan keberadaannya di satu sisi, maka dia menyatakan keberadaan pada sisi yang berlawanan, maka itu disebut dengan al-imkân al-‘âm. Misalnya, menyatakan ketidakadaan sesuatu sebagai sesuatu yang tidak ada. Secara sekilas, ini jatuh ke hukum imtinâ’ atau mustahil. Karena ketiadaannya niscaya. Tapi, melalui sudut pandang al-imkân, dia tergolong al-imkân al-‘âm. Sebab, dia masuk ke bagian kategori ketiadaan dan di saat yang sama, dia menafikan keberadaan.
Al-imkân al-‘am tergolong konsep mutlak karena tidak membutuhkan sesuatu yang lain untuk ada. Dengan kata lain, tidak butuh oposisi. Adapun yang butuh oposisi, itu seperti kontigen dan eternal, ada dan tiada, dan lain-lain.
Berdasarkan penafsiran yang dipaparkan oleh Imam Sayyid Syarif Al-Jurjani, maka pembahasan al-‘umȗr al-‘ammah itu terbatas pada masalah keberadaan, ketiadaan, hâl (antara ada dan tiada), esensi, ketersusunan, dan lain-lain. Atas dasar ini, maka deretan pembahasan tadi tergolong inti dalam ilmu kalam, bukan sekadar “mengikut”.
Uniknya, sekalipun penafsiran Imam Sayyid Syarif Al-Jurjani ini berbeda dengan Imam Adhuddin Al-Iji, justru penafsiran ini selaras dengan pembahasan ilmu kalam yang ada dalam Mawâqif yang notabenenya karya Imam Al-Iji. Hal tersebut terlihat jelas ketika kita masuk ke maqshad kedua di marshad pertama dalam mawqif pertama.
Ketiga, penafsiran ini datang dari Al-‘Allamah Muhammad bin Mubarak Syah. Menurut beliau, al-‘umȗr al-‘ammah adalah:
هي شاملة للمجرد والمادي ومقابلتهما
“(Al-‘umȗr al-‘ammah) itu mencakup hal abstak, materil, dan beroposisi dengan keduanya”
Ini seperti membahas tentang apa itu niscaya? Apa itu pasangan dari niscya? Apa itu mustahil? Apa pasangan mustahil? Dan lain-lain. Penafsiran ketiga ini merupakan konsep yang digunakan mazhab filusuf paripatetik.
Kenapa Menjadi Pembahasan Independen?
Umumnya, di buku kalam itu al-‘umȗr al-‘ammah sudah menjadi pengantar sebelum masuk ke bab ketuhanan. Namun, dijadikan pembahasan khusus karena bab ketuhanan membahas seputar hal khusus, seperti kebaruan alam, keniscayaan Tuhan, dan lain-lain. Bagaimana caranya memahami khusus jika tidak melalui pembahasan umum?
Tapi, di sebagian buku kalam untuk pemula, pembahasan ini tidak ditemukan. Sebab, sukar dipahami untuk pemula. Ulama memiliki metode tersendiri untuk mengantar para pemula berjalan ke pembahasan berat.
Mengakhirkan pembahasan berat karena alasan toleransi, itu sah-sah saja. Ini dikenal dengan taqaddum bi wadh’i (mendahulukan sesuatu sesuai dengan peletakan). Tapi, dari segi tabiat, hal ini tidak dibenarkan. Sebab, bagaimana mungkin pembahasan ketuhanan itu utuh jika tidak diantar dengan pembahasan al-‘umȗr al-‘ammah? Sudut pandang kedua ini dikenal dengan istilah taqaddum bi thab’i (mendahulukan sesuatu sesuai tabiatnya). Mengkondisikan keadaan pelajar juga tidak kalah penting.
Wallahu a’lam