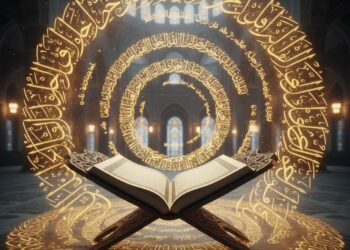Pada tulisan sebelumnya sudah dijelaskan tentang mafhum dan mashdaq, juga sudah dikatakan bahwa mashdaq itu tidak harus juz’iy (haqiqiy), bisa saja ia merupakan kulliy. Kemudian pada tulisan sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa ada lafaz yang dalam satu waktu ia menjadi kulliy, di saat bersamaan ia menjadi juz’iy (idhâfiy).
Maka pada pembahasan kali ini, kita akan membahas bagaimana keterkaitan antara dua lafaz kulliy berdasarkan mashdaq atau cakupannya. Ketika kita dipertemukan dengan dua lafaz kulliy, maka ada empat kemungkinan yang bisa terjadi, tidak lebih dari itu. Bisa saja, cakupannya sama, bisa juga yang satunya umum dan satunya khusus, bisa juga satunya umum dan satunya khusus pada satu titik lalu terpisah pada aspek lain, bahkan bisa saja tidak ada kaitannya.
Melihat ada empat kemungkinan, pembahasan ini juga dinamakan al-nisab al-arba’ (keterkaitan yang empat). Apa saja penjelasannya? Berikut ulasannya.

- Tasâwi
Tasâwi artinya sama. Dinamakan tasâwi karena dua lafaz kulliy memiliki sama-sama mashdaq yang sama keberlakuannya. Dengan ungkapan lain, kedua lafaz kulliy tersebut, sama mashdaq-nya.
Misalnya, kata insan dan basyar (sama-sama bermakna manusia) yang memiliki mashdaq yang sama. Seperti Said, Naufal, Akhir, Ulfa, Amal, dan lain-lain. Orang yang dimaksud itu, bisa menjadi mashdaq dari insan, juga bisa menjadi mashdaq dari basyar. Insan dan basyar itu adalah lafaz kulliy dan nisbah keduanya itu tasâwi (sama). Setiap insan adalah basyar dan setiap basyar adalah insan.
Contoh lain, makhluk hidup yang memiliki kemampuan berpikir dan manusia. Keduanya memiliki mashdaq yang sama, yaitu apa saja yang bisa disebut sebagai manusia. Setiap makhluk hidup yang memiliki kemampuan berpikir adalah manusia dan setiap manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan berpikir.
Karena memiliki mashdaq yang sama, sekali lagi ia dinamakan nisbah tasâwi. Pola untuk bagian ini “Setiap A adalah B dan setiap B adalah A”.
- Nisbah ‘Umum wa Khusus Muthlaq
Pada bagian ini, lafaz kulliy itu ada yang lebih umum dan lebih khusus cakupannya dan keduanya sama-sama memiliki keterkaitan. Yang satunya memiliki cakupan yang dicakup oleh lafaz kulliy yang lain dan satunya tidak. Atau lebih sederhananya, ada satu lafaz kulliy mencakup lafaz kulliy yang lainnya karena umum, sedangkan lafaz kulliy yang dicakup, tidak mencakup lafaz kulliy yang umum karena dia khusus.
Seperti kata makanan dan gorengan. Makanan itu cakupan atau mashdaq-nya bisa berupa gorengan, masakan khas, tumisan, dan lain-lain. Sedangkan gorengan sudah pasti makanan. Kalau dikemas dengan bahasa lebih mudah, gorengan sudah pasti makanan, sedangkan makanan belum tentu gorengan, bisa saja selain gorengan. Makanan lebih umum sedangkan gorengan lebih khusus.
Contoh lain, pakaian dan jilbab. Jilbab sudah pasti pakaian, sedangkan pakaian belum tentu jilbab, bisa saja baju, celana, dan lain-lain. Pakaian itu lebih umum, sedangkan jilbab lebih khusus.
Kalau kita tarik ke dalam konteks agama, kita bisa mengambil kata haram dan syirik. Haram belum tentu syirik, sedangkan syirik sudah pasti haram. Kita melihat dalam keseharian ada banyak perbuatan yang haram tapi tidak membuat orang menyekutukan Tuhan, tapi ketika perbuatan syirik itu dilakukan, pasti dapat dosa, karena syirik sudah pasti haram. Haram lebih umum, sedangkan syirik lebih khusus.
Pola untuk bagian ini “B sudah pasti A, tapi A belum tentu B”.
- Nisbah ‘Umum wa Khusus min Wajh
Jika sebelumnya keterkaitannya harus ada umum dan khusus, maka bagian ini juga ada umum dan khusus. Tapi, bertemunya pada satu titik tapi berpisah pada titik lain. Artinya, “sebagian” mashdaq pada kedua lafaz kulliy itu tercakup oleh kulliy yang lainnya, lalu sebagian lainnya tidak tercakup.
Misalnya kata mahasiswa dan muslim. Mahasiswa itu bisa saja yang Hindu, Kristen, Buddha, dan lain-lain termasuk muslim. Orang muslim juga mencakup banyak individu seperti orang muslim memiliki jabatan penguasa, orang muslim yang berprofesi sebagai dosen, dan lain-lain, termasuk mahasiswa. Tapi, keduanya dipertemukan pada “mahasiswa muslim”. Bertemu pada titik ini, tapi terpisah pada titik lain.
Misalnya lagi, orang Indonesia dan orang baik. Orang Indonesia itu bermacam-macam, ada yang baik tidak baik, ada juga yang baik. Sedangkan orang baik itu ada di banyak tempat seperti di Thailand, China, Dubai, Mesir, termasuk Indonesia. Tapi, kedua lafaz kulliy tersebut dipertemukan pada satu titik, yaitu “Orang Indonesia yang baik” lalu berpisah pada titik yang lain. Atau kemasan yang selalu kita dapatkan “Tidak semua orang Indonesia itu baik dan tidak semua orang baik itu di Indonesia” atau “Sebagian orang Indonesia itu baik dan sebagian orang baik di Indonesia”
Sekali lagi, bagian ini bertemu pada satu titik, lalu terpisah di bagian titik lain. Polanya “Tidak semua A adalah B dan tidak semua B adalah A” atau “Sebagian A adalah B dan sebagian B adalah A”. Disebut min wajh karena keumuman dan kekhususannya tampak ketika bertemu pada satu aspek atau satu titik, kalau tidak, maka tidak tampak.
- Nisbah Tabâyun
Tabâyun yang dimaksud di sini, bukan tabayun pada pembahasan sebelumnya. Tabâyun berarti berbeda atau dalam pembahasan ini bisa diartikan dengan dua lafaz kulliy yang berbeda total mashdaq-nya. Artinya, dua lafaz yang dipertemukan itu berbeda mashdaq-nya.
Seperti misalnya kata planet dan buku. Planet itu memiliki mashdaq seperti planet Bumi, Jupiter, Venus, Neptune, Merkurius, dan lain-lain. Sedangkan buku memiliki banyak mashdaq juga seperti buku hadits, buku tafsir, buku filsafat, buku logika, buku antropologi, dan lain-lain. Dari kata planet dan kata buku itu tidak memiliki kesamaan mashdaq-nya. Seperti itulah tabâyun.
Di alam semesta ini saya rasa ada banyak contoh untuk nisbah tabâyun ini. Intinya, nisbah ini kedua lafaz kulliy memiliki mashdaq yang berbeda. Polanya “A bukan B dan B bukan A” seperti “mobil bukan pulpen dan pulpen bukan mobil”.
Wallahu a’lam